"Behavioral Cartel" dan Dilema Inovasi
 Kompetisi sejati adalah fondasi inklusi ekonomi, dan melindungi kompetisi be...
Oleh Ukay Karyadi
Kompetisi sejati adalah fondasi inklusi ekonomi, dan melindungi kompetisi be...
Oleh Ukay Karyadi


Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Bayangkan Anda membeli gembok untuk melindungi toko. Yang Anda inginkan tentu gembok yang aman dan terjangkau. Masalahnya, Anda tidak tahu cara membedakan gembok berkualitas--semuanya tampak sama. Akhirnya, Anda memilih yang termurah. Beberapa minggu kemudian, toko pun dibobol.
Situasi serupa terjadi setiap hari di dunia keamanan siber (cybersecurity)--hanya taruhannya jauh lebih besar. Di era digital ini, keamanan siber bukan lagi urusan teknis tim IT semata. Keamanan siber kini menjadi masalah ekonomi struktural yang kompleks. Namun, pasar sering gagal menciptakan perlindungan memadai, terutama bagi negara berkembang dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kegagalan Pasar Berlapis
Dalam teori ekonomi, ada situasi di mana mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Keamanan siber adalah contoh sempurna kegagalan pasar berlapis. Laporan Bank Dunia Cybersecurity Economics for Emerging Markets (2023) mengungkap bahwa pasar keamanan siber merupakan contoh khas kegagalan pasar berlapis tersebut.
Pertama, masalah "pasar barang murahan" atau market for lemons. Konsep yang diperkenalkan ekonom pemenang Nobel George Akerlof (1970) ini sederhana: ketika pembeli tidak bisa membedakan kualitas produk sebelum membeli, pasar akan didominasi produk berkualitas rendah.
Di pasar keamanan siber, fenomena ini sangat nyata. UMKM serta konsumen umumnya tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengevaluasi efektivitas solusi keamanan. Mereka hanya bisa mengandalkan harga dan klaim pemasaran.
Akibatnya, vendor dengan "solusi instan" yang mempunyai klaim bombastis tapi minim proteksi justru laris manis, sementara produk berkualitas tersisih karena terlalu mahal atau terlalu kompleks. Ini bukan soal konsumen bodoh--ini soal asimetri informasi.
Kedua, masalah eksternalitas negatif yang tidak diperhitungkan. Ketika satu perusahaan tidak berinvestasi memadai dalam keamanan, mereka tidak hanya membahayakan diri sendiri--tetapi seluruh ekosistem digital. Ambil contoh serangan ransomware NotPetya tahun 2017.
Target awalnya adalah perusahaan di Ukraina, tapi serangannya menyebar ke ratusan perusahaan global--FedEx, Merck, Maersk. Total kerugian mencapai sekitar US$10 miliar. Penelitian Crosignani, Macchiavelli, dan Silva (2023) menemukan fakta mengejutkan: kerugian konsumen dan pihak ketiga empat kali lebih besar daripada kerugian perusahaan yang diserang langsung.
Ketiga, masalah barang publik. Ekonom Paul Samuelson (1954) menjelaskan ada jenis barang yang tidak akan disediakan optimal oleh pasar karena sifatnya yang non-rival dan non-excludable. Keamanan siber memiliki karakteristik ini.
Misalnya, ketika satu bank meningkatkan keamanannya, seluruh sistem perbankan menjadi lebih aman. Tapi bank tersebut tidak bisa menagih kompensasi dari bank lain yang turut menikmati manfaatnya.
Akibatnya, setiap bank punya insentif untuk "menumpang gratis" pada investasi bank lain. Hasilnya? Investasi keamanan jauh di bawah kebutuhan. Studi Gordon dan Loeb (2002) menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi optimal, perusahaan hanya menginvestasikan maksimal 37% dari kerugian yang diperkirakan untuk keamanan--jauh di bawah tingkat yang diperlukan secara sosial.
Keempat, masalah konsentrasi pasar ekstrem menciptakan kekuatan pasar (market power). Lebih dari 50% belanja keamanan siber dunia berasal dari Amerika Utara--16 kali lebih besar daripada seluruh Amerika Latin dan Karibia digabung (Canalys, 2022).
Segelintir perusahaan besar seperti Palo Alto Networks, CrowdStrike, dan Cisco mendominasi pangsa pasar global. Konsentrasi ini menciptakan dua masalah: harga yang terlalu tinggi dan produk yang tidak responsif terhadap kebutuhan pasar lokal. Negara berkembang terpaksa menggunakan produk yang dirancang untuk konteks negara maju--terlalu mahal, terlalu kompleks, atau tidak relevan dengan ancaman yang mereka hadapi.
Kelima, masalah insentif yang salah arah. Di pasar yang kompetitif berbasis kecepatan, produsen perangkat lunak punya insentif kuat untuk meluncurkan produk secepat mungkin--bukan memastikan keamanannya. Keamanan dianggap "biaya tambahan", bukan nilai jual utama. Studi SecurityScorecard dan Cyentia (2023) menemukan bahwa lebih dari 90% organisasi punya hubungan bisnis dengan setidaknya satu vendor yang pernah mengalami pelanggaran keamanan.
Mengatasi Kegagalan Pasar
Menghadapi kegagalan pasar yang kompleks tersebut, diperlukan intervensi kebijakan multi-instrumen yang saling melengkapi. Solusinya bukan sekadar regulasi tambahan, melainkan transformasi fundamental bagaimana kita memandang keamanan siber--dari tanggung jawab individual menjadi tanggung jawab kolektif.
Pertama, regulasi transparansi untuk mengatasi asimetri informasi. Ekonom pemenang Nobel Joseph Stiglitz (2000) menunjukkan bahwa kewajiban pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan efisiensi pasar.
Uni Eropa telah menunjukkan jalan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) yang mewajibkan pelaporan pelanggaran data dalam 72 jam dan memberikan denda hingga 4% pendapatan global perusahaan. Dampaknya nyata.
Penelitian Ashraf dan Sunder (2023) menunjukkan bahwa setelah GDPR diberlakukan, permintaan terhadap tenaga ahli keamanan siber meningkat signifikan, perusahaan mulai memprioritaskan keamanan sejak tahap desain produk, dan biaya modal ekuitas menurun karena berkurangnya ketidakpastian.
Untuk Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu memperkuat regulasi kewajiban pelaporan insiden siber. Pelaporan transparan akan menciptakan tekanan pasar yang mendorong investasi keamanan yang lebih baik.
Kedua, menetapkan tanggung jawab yang jelas. Perusahaan yang lalai harus menanggung konsekuensi penuh--tidak bisa sekadar mengalihkan biaya ke konsumen. Bank Indonesia telah memimpin dengan Peraturan BI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko yang mengharuskan lembaga keuangan memiliki cadangan ketahanan siber.
Ini adalah langkah benar untuk menginternalisasi eksternalitas negatif. Prinsip ini perlu diperluas ke sektor kritis lainnya: telekomunikasi, energi, transportasi, dan kesehatan. Prinsip dasarnya sederhana: jika kelalaian produsen, produsenlah yang menanggung biaya, bukan konsumen.
Ketiga, pemerintah perlu menyediakan dukungan kolektif untuk UMKM. Karena keamanan siber memiliki karakteristik barang publik, bentuk dukungannya bisa beragam: voucher keamanan siber untuk UMKM yang dapat digunakan untuk membeli jasa konsultasi atau perangkat keamanan dasar; platform nasional berbagi intelijen ancaman yang dapat diakses gratis oleh semua pelaku usaha; serta pelatihan gratis dan sertifikasi keamanan dasar.
Program "UMKM Go Digital" yang sudah berjalan perlu diintegrasikan dengan komponen keamanan siber. Tidak cukup mengajari UMKM jualan online--mereka juga harus tahu cara melindungi data pelanggan dan transaksi mereka.
Keempat, penerapan standar minimum dan sertifikasi. Sertifikasi kualitas dapat mengembalikan kepercayaan pasar pada produk berkualitas tinggi serta membantu konsumen membedakan produk yang aman. Singapura telah memimpin dengan Cybersecurity Labelling Scheme untuk perangkat pintar, sementara Uni Eropa menciptakan kerangka sertifikasi pan-Eropa melalui EU Cybersecurity Act (2019).
BSSN dapat mengembangkan Sertifikasi Keamanan Siber Nasional yang bertingkat sesuai ukuran dan kompleksitas organisasi, memberikan preferensi dalam pengadaan pemerintah untuk produk dan vendor yang bersertifikat, serta mewajibkan sertifikasi minimum sektor kritis seperti perbankan, telekomunikasi, dan layanan publik digital. Dengan standar yang jelas dan terukur, pasar dapat berfungsi lebih baik karena konsumen memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan.
Kelima, mendorong ekosistem lokal melalui kebijakan industri tepat. Ekonom Ha-Joon Chang (2002) menunjukkan bahwa negara-negara maju secara historis menggunakan infant industry protection untuk membangun kapasitas domestik sebelum membuka pasar. Dalam konteks keamanan siber, ini bukan tentang proteksionisme melainkan strategic industrial policy.
Keenam, koordinasi kelembagaan untuk mengatasi masalah collective action. Ekonom Mancur Olson (1965) menunjukkan bahwa dalam kelompok besar, individu memiliki insentif untuk free riding dan tidak berkontribusi pada public goods. Dalam konteks keamanan siber, ini berarti organisasi individual tidak akan sukarela berbagi informasi ancaman atau berkoordinasi--padahal koordinasi adalah kunci efektivitas pertahanan.
Ekonom Elinor Ostrom, peraih Nobel 2009, menunjukkan bahwa sumber daya bersama dapat dikelola efektif melalui institusi dengan karakteristik tertentu: batas yang jelas, monitoring, sanksi bertingkat, dan mekanisme resolusi konflik. Pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan forum kolaborasi antar sektor, seperti Information Sharing and Analysis Center (ISAC), yang memungkinkan pertukaran informasi ancaman secara aman dan terstruktur.
Jadi, jelaslah bahwa keamanan siber bukan hanya masalah teknis. Ini adalah masalah ekonomi, sosial, dan politik sekaligus. Pasar tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri--karena insentif individual tidak selaras dengan kebutuhan kolektif.
Seperti diingatkan Gordon dan Loeb (2002): "Keamanan siber bukan hanya barang privat--ini masalah keamanan ekonomi nasional." Untuk menjaganya, kita butuh lebih dari mekanisme pasar. Kita butuh kontrak sosial baru yang menempatkan keamanan siber sebagai hak dan tanggung jawab kolektif.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita perlu bertindak, melainkan seberapa cepat implementasi solusi-solusi tersebut. Setiap hari yang berlalu tanpa kebijakan yang memadai adalah hari di mana kita membiarkan gembok murahan melindungi aset paling berharga kita: data, privasi, dan kedaulatan digital bangsa.
Saatnya kita membangun pasar yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan adil bagi semua.
 Kompetisi sejati adalah fondasi inklusi ekonomi, dan melindungi kompetisi be...
Oleh Ukay Karyadi
Kompetisi sejati adalah fondasi inklusi ekonomi, dan melindungi kompetisi be...
Oleh Ukay Karyadi
 Bagi RI, pertanyaannya bukan lagi apakah "kartel siluman" telah te...
Oleh Ukay Karyadi
Bagi RI, pertanyaannya bukan lagi apakah "kartel siluman" telah te...
Oleh Ukay Karyadi
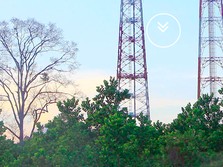 Kedaulatan telekomunikasi bukan lagi sekadar jargon normatif dalam ranah keb...
Oleh Ridwan Syahrani Amrullah
Kedaulatan telekomunikasi bukan lagi sekadar jargon normatif dalam ranah keb...
Oleh Ridwan Syahrani Amrullah
 "serakahnomics" mencerminkan simbiosis antara kekuasaan politik (p...
Oleh Ukay Karyadi
"serakahnomics" mencerminkan simbiosis antara kekuasaan politik (p...
Oleh Ukay Karyadi