4 Pilar Kedaulatan Digital RI: Semikonduktor, AI, Siber, dan Cloud
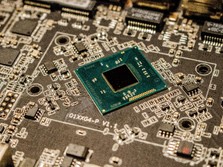 Empat pilar kedaulatan digital adalah tiket untuk melompat ke depan, menjadi...
Oleh Kuntjoro Pinardi
Empat pilar kedaulatan digital adalah tiket untuk melompat ke depan, menjadi...
Oleh Kuntjoro Pinardi


Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Beberapa waktu ini, muncul dokumentasi di berbagai media internasional yang menunjukkan bagaimana kendaraan udara nirawak (UAV) berbiaya rendah serta drone berukuran kecil mampu mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah maupun mendukung pasukan Ukraina untuk menahan laju serangan Rusia di medan perang.
Perkembangan peperangan saat ini seolah memberi kesan bahwa upaya untuk menghalangi musuh atau memenangkan perang dapat dilakukan dengan peralatan pertahanan dengan biaya rendah atau low-cost.
Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, tertarik mempertimbangkan sistem pertahanan yang lebih terjangkau untuk menghemat anggaran yang terbatas. Meski pendekatan ini mungkin tepat dalam proses akuisisi drone atau loitering munitions, sering kali hal tersebut menyembunyikan risiko besar ketika menyangkut persyaratan kinerja sistem pertahanan utama.
Sebenarnya, gagasan utama di balik pengadaan sistem pertahanan berbiaya rendah adalah untuk melakukan penghematan. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa hal ini dapat membantu pemerintah untuk fokus pada penambahan kuantitas, sehingga mampu mengakuisisi lebih banyak aset dengan jumlah alokasi anggaran yang sama.
Namun, realitas di lapangan berbeda. Pola ini memang dapat bekerja untuk beberapa jenis alutsista, misalnya seperti UAV atau loitering munitions, tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk proses akuisisi sistem pertahanan utama.
Faktanya, pilihan yang "lebih terjangkau" atau low-cost justru sering berakhir menjadi lebih mahal, karena alutsista tersebut membawa biaya lifecycle yang lebih tinggi. Dengan kata lain, seiring waktu, masa penggunaan bisa memiliki biaya lebih besar dari yang diperkirakan. Hal ini kemudian menyebabkan lebih banyak operasi pemeliharaan yang perlu dilakukan dan umur operasional yang lebih pendek, sehingga menyebabkan pensiun dini bagi beberapa alutsista.
Masalah lain berkaitan dengan kesenjangan kinerja operasional. Platform atau sistem kelas rendah sering kali kurang memiliki daya tahan, presisi, atau kemampuan bertahan dibandingkan dengan yang alutsista kelas tinggi.
Memang benar bahwa sistem pertahanan kelas tinggi akan memiliki biaya yang lebih tinggi. Namun, tingginya biaya tersebut merupakan hasil dari proses penelitian dan pengembangan (R&D) yang dilakukan secara bertahun-tahun, termasuk pembuatan prototipe serta pengujian lapangan sebelum alutsista masuk ke tahap produksi.
R&D ini, meski mungkin tidak terlihat oleh pembeli, sebenarnya sangat penting untuk memastikan bahwa platform dan sistem pertahanan dapat diandalkan serta mampu bertahan dalam lingkungan konflik berintensitas tinggi.
Sementara itu, sistem berbiaya rendah sering kali hadir dengan kinerja rendah, kemampuan interoperabilitas yang terbatas, serta masalah integrasi. Hal ini disebabkan karena sistem "low-cost" biasanya dirancang sebagai solusi mandiri, bukan untuk interoperabilitas, sehingga menimbulkan kesulitan ketika perlu diintegrasikan dengan armada yang ada.
Misalnya, data radar kapal perang yang tidak dapat dikirimkan ke pusat operasi angkatan laut untuk membentuk Recognised Maritime Picture (RMP), atau baterai pertahanan udara yang menjadi "buta" karena tidak dapat mengakses data sensor dari pesawat tempur atau radar Ground Control Interception (GCI) secara real time.
Situasi seperti ini bukan hanya tidak efisien, tetapi juga bisa menjadi beban strategis. Bahkan dengan adanya solusi seperti domestic datalink, integrasi sistem pertahanan mandiri biasanya tidak semudah pembaruan software, sebab proses tersebut akan membutuhkan perancangan ulang arsitektur datalink secara keseluruhan dengan biaya yang sangat tinggi.
Kekhawatiran lain dari sistem pertahanan berbiaya rendah adalah kerentanannya secara strategis. Untuk dapat menyediakan peralatan pertahanan utama dengan biaya lebih terjangkau, produsen harus memangkas biaya di aspek tertentu.
Jika bukan pada produknya, R&D, atau kemampuannya untuk diintegrasikan dengan armada, maka kemungkinan ada kerentanan strategis lain yang harus diantisipasi. Dalam beberapa kasus, harga yang lebih rendah atau terjangkau dapat terjadi karena produk tersebut mendapat manfaat dari R&D asing.
Beberapa contoh seperti rudal balistik taktis Türkiye, Khan, sebenarnya berasal dari rudal buatan China, B-611, dan diproduksi dengan lisensi di Türkiye. Walaupun implikasinya untuk rudal balistik jarak pendek mungkin terbatas, risiko ini jauh lebih besar ketika menyangkut platform pertahanan utama dan aset strategis penting seperti kapal perang, radar, pesawat tempur, atau kapal selam.
Dalam kasus seperti ini, pihak lawan yang berkontribusi dalam proses desain atau pengembangan platform mungkin akan lebih memahami keterbatasannya alutsista tersebut, sehingga mereka dapat mengembangkan langkah perlawanan yang efektif bahkan sebelum konflik dimulai.
Selain itu, peralatan berbiaya rendah biasanya dikirim dalam konfigurasi terbatas. Misalnya, kapal perang yang hanya memiliki konfigurasi Fitted For But Not With (FFBNW) untuk beberapa sistem senjata utama.
Dalam praktiknya, penghematan harga awal ini kemudian diimbangi dengan retrofit yang mahal serta celah operasional. Lebih jauh lagi, opsi murah hampir pasti kurang mampu menghadapi ancaman baru, seperti perang siber.
Perlu diingat, semakin banyak platform pertahanan modern di era kini yang berbasis software dan saling terhubung satu sama lain, sehingga cenderung lebih rentan terhadap peretasan, gangguan, bahkan pemutusan kendali jarak jauh.
Sistem atau platform yang disebut modern tetapi tanpa memiliki arsitektur keamanan siber yang kuat, misalnya sistem komunikasi yang aman, datalink yang terlindungi, sistem deteksi intrusi, serta protokol pemulihan cepat, berisiko dapat dilumpuhkan dengan mudah.
Di era ketika beberapa pihak yang saling berlawanan dapat merusak sensor, memasukkan data palsu ke dalam sistem penembakan, atau mengganggu jaringan logistik, ketiadaan ketahanan siber membuat platform murah berubah menjadi liabilitas strategis.
Pada akhirnya, para pengambil keputusan sebaiknya perlu mempertimbangkan pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan, bukan sekadar mengutamakan faktor biaya yang terjangkau. Meskipun efektivitas biaya dan harga memang termasuk indikator penting, proses pengadaan harus selalu mempertimbangkan kinerja, dampak strategis, serta keberlanjutan sebagai indikator utama dalam menilai peralatan atau platform baru.
Pada dasarnya, low-cost dalam pertahanan biasanya tidak menyelesaikan masalah. Hal ini bahkan lebih penting bagi negara seperti Indonesia, yang terletak di wilayah strategis dengan lingkungan yang penuh sengketa, serta harus mempertahankan kepentingan kedaulatan nasional.
Sebaliknya, modernisasi angkatan bersenjata dengan platform berbiaya rendah bisa dianggap sebagai tanda kelemahan, bukan kekuatan, sehingga pada akhirnya berpotensi mengundang provokasi pihak lawan alih-alih mencegahnya.
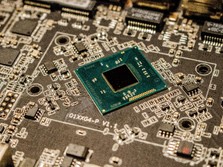 Empat pilar kedaulatan digital adalah tiket untuk melompat ke depan, menjadi...
Oleh Kuntjoro Pinardi
Empat pilar kedaulatan digital adalah tiket untuk melompat ke depan, menjadi...
Oleh Kuntjoro Pinardi
 Diplomasi intelijen adalah bentuk khusus diplomasi yang berlangsung secara r...
Oleh Aryo Bimo Prasetyo
Diplomasi intelijen adalah bentuk khusus diplomasi yang berlangsung secara r...
Oleh Aryo Bimo Prasetyo
 Proses pengambilan keputusan pengadaan pesawat tempur hendaknya mempertimban...
Oleh Alman Helvas Ali
Proses pengambilan keputusan pengadaan pesawat tempur hendaknya mempertimban...
Oleh Alman Helvas Ali
 Selama 10 tahun terakhir, Jakarta tidak banyak melakukan belanja sistem senj...
Oleh Alman Helvas Ali
Selama 10 tahun terakhir, Jakarta tidak banyak melakukan belanja sistem senj...
Oleh Alman Helvas Ali